Mencari Keadilan dalam Masyarakat Majemuk
Mencari Keadilan dalam Masyarakat Majemuk Empat Model Keadilan Politis”, F. Budi Hardiman
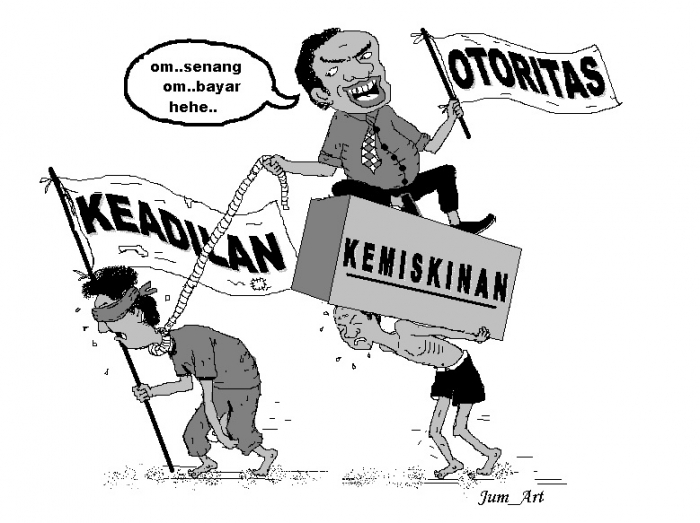
Oleh : Ahmad Faisal
Jika di Eropa
etnosentrisme dan fundamentalisme agama menjadi daya sihir baru pasca
runtuhnya Unisoviet, maka di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru
dianggap menjadi pemicu relativisme nilai-nilai dengan adanya
desentralisasi dan otonomi daerah. Semuanya terkerucutkan dalam sebuah
istilah yang dinamakan keadilan. Keadilan menjadi penting karena di
Indonesia masyarakatnya cenderung majemuk, sementara itu ada banyak kata
“ingin” yang dilontarkan oleh setiap jenis orang/kelompok dalam
kemajemukan tersebut. Secara garis besar, ada empat macam keadilan
politis yang ditayangkan oleh F. Budi Hardiman, yaitu keadilan
komunitarian, liberal, multikultural, dan dilengkapi dengan keadilan
transformasional. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana keadilan dapat
diwujudkan dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia?
Pertama,
model keadilan komunitarian di dalamnya terdapat perjuangan untuk
mengangkat politik pengakuan yang menginginkan konsep pra politis suatu
kelompok menjadi keadilan politis. Dalam hal ini, nilai keutamaannya
adalah komunitas religo-kultural yang diangkat secara politis, bukan
kesepakatan politis yang diinginkan. Sehingga dapat menimbulkan
supremasi hukum agama mayoritas atas hukum negara, seperti kalau di
Indonesia munculnya aliran Islam Ahmadiyah, misalnya. Keadilan kedua,
yaitu keadilan liberal yang menekankan adanya netralitas posisi negara
di hadapan orientasi nilai partikular etnis dan religius. Pada model
ini negara harus cermat dan mementingkan politik
redistribusi/redistribusi sosial daripada politik pengakuan.
Keadilan multikultural merupakan jenis keadilan ketiga.
Pada keadilan multikultural, negara tetap bersifat liberal, hak-hak
kosmopolitan individu dijamin, namun negara juga menjamin hak-hak
kultural kelompok. Keadilan multikultural berarti memberikan hak-hak
kolektif yang sama kepada semua kelompok kultural untuk memelihara dan
mengungkapkan tradisi dan identitas kolektif mereka. Selanjutnya, keempat
adalah keadilan transformasional usulan Hardiman yang dirasa lebih
cocok untuk masyarakat majemuk dunia ketiga yang sedang terglobalisasi
seperti masyarakat Indonesia.
Pandangan ini mengacu
pada dua teori, yaitu teori diskursus Jurgen Habermas dan
dekonstruktivisme Jacques Derrida. Titik tolaknya adalah bahwa dalam
kenyataan demokrasi, pandangan pra politis tentang keadilan dapat dan
harus ditransformasikan. Dalam teori diskursus, para warga negara dari
berbagai macam kelompok etnis maupun religius diposisikan berdiri setara
dalam proses komunikasi publik untuk mengambil keputusan publik. Jika
dari teori dekonstruktivisme keadilan yang dimaksud adalah suatu
keprihatinan dan tanggung jawab tak terbatas untuk mendengarkan yang
lain dalam keberlainannya.
Artinya, kedua teori
tersebut dalam hal ini keadilan transformasional adalah suatu upaya
untuk memenuhi tuntutan kesamaan sekaligus satu sikap yang tepat
terhadap kemajemukan cara-cara hidup di dalam masyarakat. Yang
membedakan terutama dengan keadilan liberal adalah keadilan
transformasional memposisikan aspirasi kelompok etnis maupun eligius
sebagai titik tolak komunikasi publik. Namun, tidak serta merta hak
kolektif diproteksi, tetapi didorong untuk komunikasi karena hak-hak
komunikasi mendapat prioritas seperti halnya menurut Nancy Fraser bahwa
semua kelompok sosial, etnis, maupun religius memiliki status yang
setara dan hak komunikasi yang sama dalam demokrasi.
Hak komunikasi
yang ada nampaknya memberikan dimensi hak azasi manusia dalam proses
penentuan kebijakan publik. Perspektif etnosentrisme harus
dikesampingkan dan dalam prosesnya ada keberlainan yang tidak sedikit.
Sehingga, perlu adanya ‘mendengarkan yang lain’ agar berbagai kelompok
dapat melihat norma dan konsep pra politis itu dalam dimensi HAM.
Keadilan politis
bukan diletakkan di masa lalu ataupun masa kini, tetapi di masa depan.
Karena dari teori Derrida mengatakan bahwa keadilan terlaksana justru
jika suatu tindakan menuntut kita untuk mengikuti sistem aturan,
keadilan menuntut kita untuk melakukan interpretasi atas aturan
seolah-olah kita adalah penemu aturan yang baru. Adanya fakta
pluralitas mengharuskan setiap agama melihat dirinya melalui sudut
pandang pihak lain. Hal ini sejalan dengan tuntutan demokrasi bahwa
berbagai kelompok dalam masyarakat majemuk berupaya keras untuk mencapai
saling pengertian. Atau dalam istilah Habermas, pada diskursus
rasional kelompok-kelompok yang cenderung keras kepala harus
merelatifkan pandangan-pandangannya untuk mentransformasikan norma-norma
komunitasnya yang dianggap eksklusif menjai keadilan politis yang
melampaui kelompok partikular.
Comments
Post a Comment